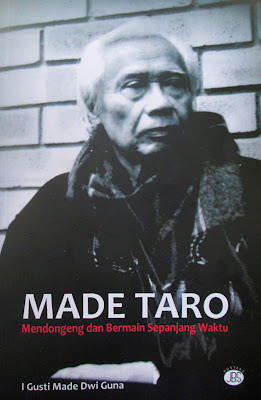Banyak bank umum nasional dengan tawaran produk menarik, memang. Tak sedikit pula lembaga keuangan yang memiliki pelayanan berkelas hingga membuat nasabahnya bak raja. Tapi, saya memilih bersetia pada Bank Nasional Indonesia (BNI) 1946. Dan, Pengalaman Bersama BNI itu sudah mencapai 14 tahun.
Ya, 14 tahun sudah saya menjadi nasabah Taplus BNI. Saya nyaris lupa berapa kali sudah berganti buku tabungan. Saya pun hampir tak ingat, berapa kali sudah mengganti kartu ATM BNI.
Namun, saya sedikit ingat, perjumpaan saya dengan BNI terjadi sekitar tahun 2002, dua tahun menjelang tamat dari bangku kuliah di Jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra, Universitas Udayana. Bermula dari pengalaman membayar SPP kuliah saban semester melalui BNI, akhirnya saya memutuskan membuka rekening BNI saja. Kala tiba waktu membayar SPP, saya tinggal debet saja.
 |
| Buku tabungan BNI Taplus dan ATM BNI yang saya miliki. |
Itulah kali pertama saya memiliki rekening di bank umum nasional. Sebelumnya, saya hanya memiliki rekening bank lokal. Maklum, kala itu kekhawatiran terhadap kebangkrutan sebuah bank seperti pernah terjadi kala krisis ekonomi tahun 1997 membiakkan trauma pada diri saya. Pilihan terhadap BNI pun dibayang-bayangi kekhawatiran semacam itu. Tapi, dalam pikiran saya saat itu, BNI relatif aman karena termasuk bank milik pemerintah.
Ternyata, pilihan terhadap BNI tidak keliru. Malah, pada tahun-tahun kemudian, rekening BNI yang saya miliki menjelma berkah. Manakala melanjutkan kuliah S2 di Program Studi Magister Ilmu Linguistik Konsentrasi Wacana Sastra di Pascasarjana Universitas Udayana tahun 2008, rekening BNI saya benar-benar fungsional. Segala pembayaran SPP dan biaya perkuliahan di kampus ternyata melalui BNI. Tentu saja semua urusan pembayaran kuliah jadi kian mudah, makin cepat.
Selain itu, kemudahan menjangkau kantor cabang dan ATM menjadi asalan saya memilih BNI. Tahun 2002, saya indekos di Jalan Kebo Iwa. Kala itu, BNI memiliki kantor cabang di Jalan Buluh Indah. ATM-nya juga banyak tersedia di kawasan Jalan Gatot Subroto Barat.
Tak hanya itu, rekening BNI juga memiliki arti penting manakala saya menerima beasiswa Kajian Tradisi Lisan (KTL) dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional pada tahun kedua kuliah S2. Transfer dana beasiswa juga dilakukan melalui rekening BNI.
Bukan hanya saya yang bersetia pada BNI, ternyata. Banyak teman sesama dosen, baik di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS), juga sejak lama memiliki rekening BNI. Sebagian besar teman dosen di PTN memiliki rekening BNI karena gaji dan tunjangan mereka ditransfer melalui BNI. Sementara banyak teman dosen di PTS yang memiliki rekening BNI karena menerima tunjangan sertifikasi dosen dari pemerintah melalui BNI.
"Kalau jadi dosen, ya, harus punya rekening BNI. Rekening BNI itu ibarat pundi wajib bagi dosen," kata Ida Ayu Agung Ekasriadi, salah seorang teman dosen di IKIP PGRI Bali.
Saya pun mengalami hal itu pada tahun 2016 ini, manakala mulai menerima tunjangan sertifikasi dosen. Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah VIII mensyaratkan kepemilikan rekening BNI bagi penerima tunjangan sertifikasi dosen. Ini rasa syukur berikutnya dari saya atas perjalanan panjang bersama BNI.
Dana hibah penelitian yang kerap diperebutkan para dosen pun lebih sering disalurkan melalui BNI. Itu sebabnya, banyak dosen yang lebih memiliki rekening BNI. Teman-teman saya sesama dosen di IKIP PGRI Bali, sebagian besar memiliki rekening BNI.
Para mahasiswa yang saya ajar pun tak sedikit yang memiliki rekening BNI tinimbang rekening bank lain. Alasannya tak jauh berbeda dengan saya: aktivitas pembayaran perkuliahan lebih sering melalui rekening BNI. Banyak lembaga pendidikan tinggi yang menjadikan BNI sebagai bank mitra untuk melayani pembayaran biaya pendidikan mahasiswanya.
Tahun 2016 ini, saya juga mulai menempuh pendidikan S3 di Program Studi Doktor Linguistik, Konsentrasi Wacana Sastra di Pascasarjana Universitas Udayana. Biaya pendaftaran, SPP dan biaya-biaya lain juga dilayani melalui BNI. Lagi-lagi ini membuktikan pilihan menjadi nasabah BNI adalah pilihan tepat bagi mereka yang sedang menempuh pendidikan.
Itu sebabnya, tampaknya tak keliru jika saya sebut BNI sebagai "bank para cendekia", "bank orang-orang terpelajar", "bank kaum terdidik". Mereka yang sedang menempuh pendidikan, menjadi pendidik maupun tenaga kependidikan umumnya menjadi nasabah BNI.
Produk-produk BNI juga dekat dengan bidang pendidikan. Tappenas BNI misalnya, cocok digunakan untuk menyiapkan tabungan pendidikan anak-anak. Belakangan ada Simpel (Simpanan Pelajar) yang menjadi program wajib bagi bank-bank nasional untuk mensosialisasikan kegiatan menabung bagi anak-anak sekolah. BNI juga memiliki Taplus Anak dan Taplus Muda yang memiliki sejumlah keunikan tersendiri dibandingkan produk-produk lainnya. Dalam layanan kredit, BNI juga memiliki kredit khusus biaya pendidikan. Namanya BNI Cerdas.
Bukan hanya itu. BNI juga seringkali memanjakan nasabahnya melalui hadiah maupun promo pada momen tertentu. Menariknya, promo itu sangat dekat dengan kalangan terdidik. Rasa syukur saya bertambah sebagai nasabah BNI karena bank ini memberikan promo diskon 10% saat berbelanja buku di Toko Buku Gramedia menggunakan kartu debit BNI. Saya tergolong doyan berbelanja buku di Gramedia. Yang paling menggembirakan saat peringatan Hari Buku Nasional, 17 Mei 2016 lalu. Saya menerima pesan pendek (SMS) mengenai promo diskon 30% bagi pengguna kartu kredit atau debit BNI di Toko Buku Gramedia. Tepat di hari terakhir diskon, 19 Mei 2016, saya pun menyambangi Gramedia menuntaskan rencana membeli sejumlah buku untuk saya dan anak. Seharusnya saya membayar buku itu dengan harga total Rp 249.000, tapi karena menggunakan kartu debit BNI, saya hanya membaya Rp 174.500. Penghematan dari BNI yang patut disyukuri, tentu saja.
 |
| Buku-buku yang saya beli di Gramedia dan bukti struk pembayaran via debet kartu Debit BNI |
Kepercayaan kalangan terdidik Indonesia terhadap BNI 46 tampaknya tak lepas dari sejarah panjang BNI yang tahun ini memasuki usia 70 tahun: #70TahunBNI. Di mata nasabah, rekam jejak yang panjang tentu menjadi pertimbangan. Terlebih lagi BNI merupakan bank umum nasional pertama yang dimiliki pemerintah. Bahkan, hari kelahiran BNI pada 5 Juli 1946 diperingati sebagai Hari Bank Nasional. Unsur sejarah dan dukungan pemerintah tentu saja membuat para kaum cerdik-cendekia yakin menjadikan BNI sebagai sahabat mereka.
Fakta tentang nasabah kaum cendekia, terpelajar atau terdidik selayaknya dibaca BNI sebagai keunggulan komparatif yang harus dipertahankan. BNI mesti menjaga kepercayaan para nasabah dari kelompok menengah ini. Caranya, mengintensifkan produk-produk khusus bagi kalangan pelajar, mahasiswa, guru, dosen maupun tenaga kependidikan. Jika itu dilakukan, BNI akan mengukuhkan citranya sebagai Bank Para Cendekia, Bank Kaum Terpelajar, Bank Golongan Terdidik.
Selamat hari jadi ke-70 BNI 46. Jangan pernah lelah memberi yang terbaik pada Indonesia!